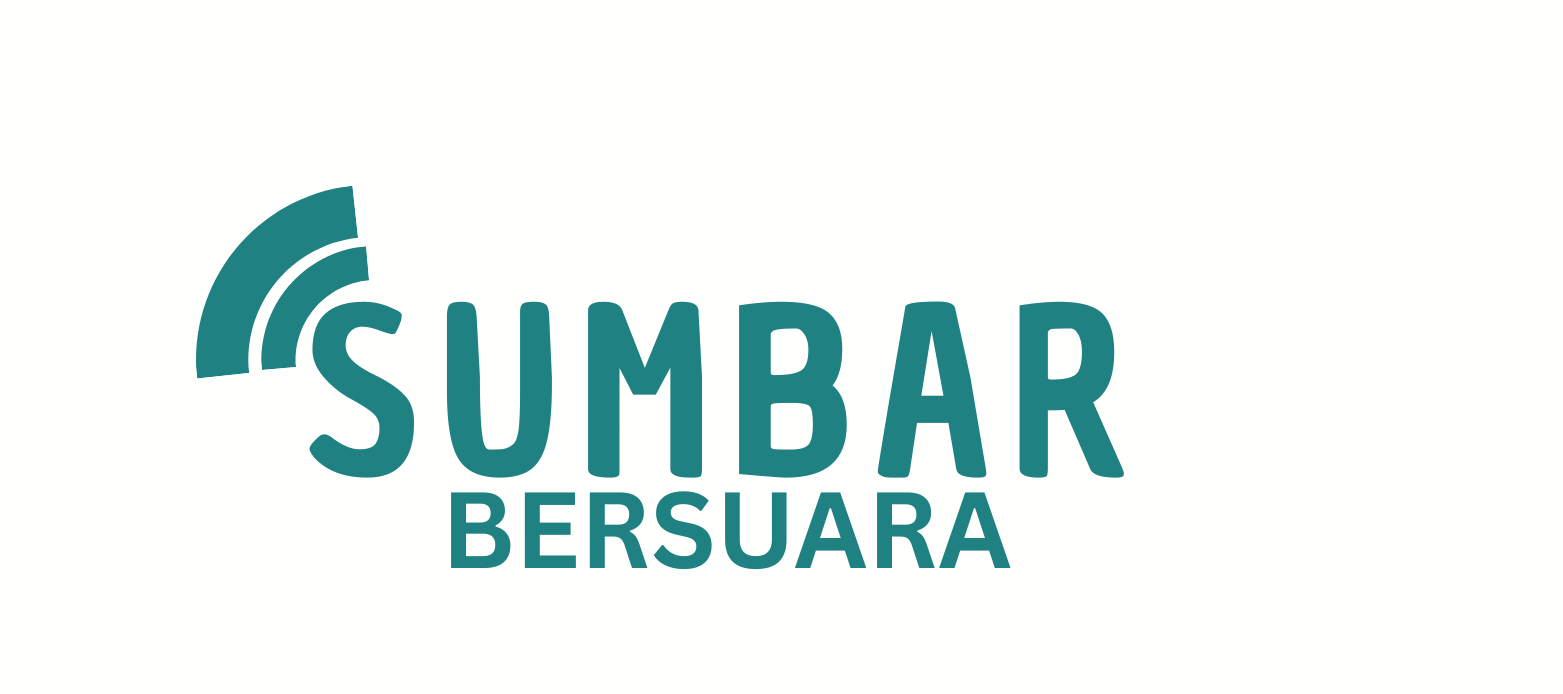Oleh: Redho Rama P, S. Ip, M. Ip
Sekretaris KNPI Kota Padang
Kota Padang seharusnya sunyi seperti biasa. Tapi ada yang tidak biasa: kabar tentang perusakan tempat ibadah menyebar lebih cepat dari suara azan dan lonceng gereja. Saya, yang lahir dan tumbuh di tanah ini, hanya bisa terdiam. Bukan karena kaget—melainkan karena sadar, kita memang belum selesai berdamai dengan diri sendiri.
Sumatera Barat, apalagi Padang, dikenal sebagai tanah yang religius. Tapi di balik kebanggaan itu, seringkali kita lupa bahwa religiusitas sejati tak bisa diukur dari jumlah rumah ibadah, panjang sajadah, atau kerasnya suara toa. Kita belum benar-benar belajar tenang dalam menghadapi perbedaan. Kita masih mudah terbakar oleh desas-desus, lebih gemar menghakimi ketimbang memahami. Kita masih sering menyamakan kritik dengan serangan, dan perbedaan keyakinan sebagai ancaman.
Ini bukan soal siapa mayoritas, siapa minoritas. Bukan pula soal siapa yang lebih lama tinggal atau siapa yang lebih keras bersuara. Ini adalah soal bagaimana kita hidup selaras—saling mengenali, saling menghargai, dan membiarkan ruang yang cukup untuk damai tumbuh di antara kita. Sebab sejarah tak pernah bertanya kita kelompok apa; ia hanya mencatat, siapa yang memilih merusak, dan siapa yang berusaha menjaga.
Saya melihat sendiri—di warung-warung kopi, di lapau, di ruang-ruang pemuda lintas iman—anak-anak muda bisa duduk bersama tanpa beban. Nonton bola bareng, bercanda soal makanan halal-haram dengan tawa, bukan kebencian. Tapi semua kedamaian itu bisa runtuh dalam sekejap, hanya karena satu pesan berantai, satu unggahan tanpa verifikasi, satu bisikan penuh curiga. Kadang, yang lebih mengerikan dari perusakan adalah cara kita menikmati kekacauan dengan penuh diam.
Apa yang terjadi di Kota Padang bukan hanya soal dinding tempat ibadah yang dirusak. Itu adalah retakan dalam rumah batin kita sendiri. Retakan yang menunjukkan bahwa fondasi sosial kita rapuh. Bahwa pendidikan toleransi tak pernah benar-benar masuk ke dalam rumah-rumah, ke meja makan, ke pergaulan kita sehari-hari. Bahwa ruang musyawarah masih dikalahkan oleh penghakiman sepihak di grup WhatsApp.
Sosiolog Ralf Dahrendorf pernah mengatakan: konflik bukanlah penyakit dalam masyarakat—ia adalah denyut yang wajar dari ketimpangan yang belum selesai. Konflik muncul karena ada relasi kuasa yang timpang, karena ada yang merasa tak didengar. Ketika identitas dijadikan alat untuk menunjukkan siapa yang berhak atas ruang dan siapa yang tidak, maka yang lahir bukanlah kedamaian, tapi dominasi. Dan dominasi, cepat atau lambat, akan memicu letupan.
Namun, Dahrendorf juga percaya: perubahan bisa lahir dari konflik—asal disalurkan dengan adil. Tapi jika dendam diternak dalam diam, kalau kecurigaan dibiarkan tumbuh dalam senyap, maka ledakannya akan datang dalam bentuk destruktif—seperti yang kita saksikan hari ini.
Di sisi lain dunia, puluhan tahun lalu, John Lennon menulis lagu yang mengajak kita membayangkan dunia tanpa batas: Imagine there’s no heaven… no religion too. Lennon bukan ingin menghapus iman, melainkan membayangkan dunia yang tak saling menyakiti hanya karena cara mereka menyebut nama Tuhan berbeda. Dalam Give Peace a Chance, ia menyanyikan pesan sederhana: damai itu mungkin, jika kita memberi ruang.
Bob Marley, dengan dreadlock, gitar, dan senyum tenangnya, menyampaikan hal serupa dari sisi yang lebih membumi: You can’t separate peace from freedom, because no one can be at peace unless he has his freedom. Dan dalam Redemption Song, ia berbisik kepada kita semua: Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Sebab terkadang, yang harus kita bebaskan bukan orang lain—tapi diri sendiri, dari ketakutan dan kebencian yang diwariskan.
Mahatma Gandhi, dalam perjuangannya yang sunyi namun keras kepala, pernah mengingatkan: “You may never know what results come of your actions. But if you do nothing, there will be no result.” Kita memang tak selalu tahu apakah sikap damai yang kita pilih hari ini akan langsung mengubah keadaan. Tapi jika kita memilih diam, membiarkan amarah dan prasangka tumbuh subur, maka hasilnya justru pasti: perpecahan. Sebab, seperti kata Gandhi pula, “The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace.”
Saya percaya, Padang bisa lebih dari ini. Kita punya tradisi musyawarah yang hangat di lapau-lapau, tempat orang tua dulu menyelesaikan masalah dengan kopi dan kata, bukan dengan kekerasan dan fitnah.
Mungkin ini waktunya kita berhenti merasa paling benar. Waktunya kita lebih banyak mendengar, lebih sabar memahami. Waktunya pemuda mengambil peran sebagai jembatan—bukan sebagai tembok. Karena jika hari ini kita membiarkan konflik memecah ruang hidup bersama, esok yang hilang bukan hanya rasa aman—tapi juga kemampuan kita untuk saling memahami dan hidup dalam keserasian.
Sebab pada akhirnya, konflik tak pernah benar-benar melahirkan pemenang. Ia hanya menyisakan abu bagi yang kalah, dan arang bagi yang menang.